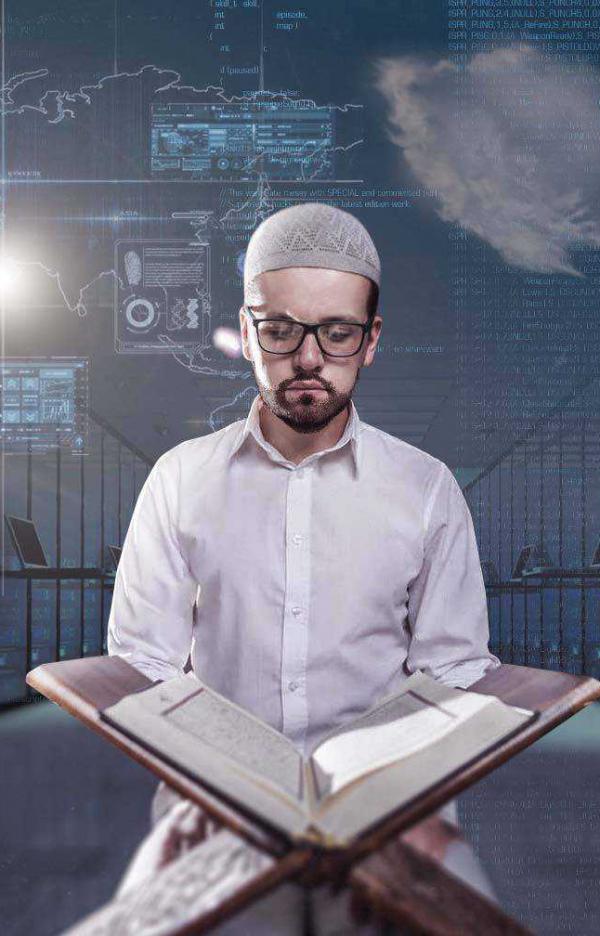—Syed Muhammad Naquib al-Attas1
A. Pendahuluan
Diskursus mengenai al-Qur’an dan hadist Nabi, sejak zaman dahulu hingga saat ini selalu menarik untuk diperbincangkan. Selain sebagai sumber tertinggi dari ilmu pengetahuan,2 keduanya juga diriwayatkan dari berita yang benar (khabar á¹£Ädiq) yang bersifat absolut (absolute authority)3 sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan validitasnya. Namun, banyak sarjana Barat (baca: orientalis) yang menuduhnya sebagai sumber yang palsu dan tidak otentik. Hal ini didasari atas asas dasar epistemologi4 mereka yang terbatas, yaitu hanya bersumber dari pancaindra dan akal semata.5 Keterbatasan asas dasar epistemologi ini berdampak kepada kesimpulan atas autentikasi dan validitas ilmu pengetahuan.
Berbeda dengan Barat, di dalam epistemologi Islam, selain pancaindra dan akal, sumber ilmu pengetahuan juga melingkupi intuisi dan kabar yang benar atau yang biasa disebut dengan khabar á¹£Ädiq (true report).6 Di sini tampak bahwa dimensi epistemologi Islam lebih kaya dan jauh lebih luas. Hal ini juga berarti, tradisi khabar á¹£Ädiq hanya dapat ditemukan di dalam epistemologi Islam. Dengan tradisi khabar inilah al-Qur’an dan hadist menjadi sumber yang tetap otentik dan terjaga keasliannya dari dahulu kala hingga saat ini.
Bukan tanpa alasan jika para orientalis bersikap ragu-ragu kepada al-Qur’an dan hadist. Mereka berasumsi bahwa ilmu pengetahuan yang bersumber dari khabar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Arthur Jeffery misalnya, menganggap bahwa sejarah kodifikasi al-Qur’an adalah fiktif serta meragukan keabsahan Mushaf Utsmani.7 Hal yang serupa juga diungkapkan oleh William Muir—seorang orientalis berdarah Inggris—yang menganggap dalam literatur hadist, nama Nabi Muhammad SAW sengaja dikutip untuk menutupi kebohongan serta berbagai keganjilan-keganjilan.8
Pernyataan yang serupa juga dikemukakan oleh seorang orientalis kebangsaan Inggris, Alfred Guillaume. Ia mengatakan sangat sulit untuk mempercayai literatur hadist secara keseluruhan sebagai sebuah rekaman yang betul-betul otentik, bahwa semua berasal dari perbuatan serta perkataan Rasulullah SAW.9 Joseph Schacht juga mengemukakan tuduhan yang kurang lebih serupa bahwa tidak ada hadist yang benar-benar terbukti asli dari Nabi Muhammad.10 Ia juga berasumsi bahwa hadist baru muncul pada abad kedua hijriah,11 serta meragukan keaslian hadist-hadist yang tertulis dalam al-kutÅ«b al-sittah.12 Di sini, Schacht secara tidak langsung tidak hanya meragukan hadist, tetapi juga menuduh para perawi sebagai pendusta yang menyembunyikan kebenaran dengan mengarang cerita dan berita. Dengan kata lain, argumen para orientalis yang telah disebutkan sebelumnya mengindikasikan keraguan bahkan ketidakpercayaan akan keaslian al-Qur’an dan hadist, yang autentikasinya diriwayatkan oleh kabar yang benar (khabar á¹£Ädiq).
Untuk itu, tulisan ini berusaha menjawab asumsi-asumsi, preposisi-preposisi serta tuduhan-tuduhan para orientalis di atas yang menafikan berita yang benar (khabar á¹£Ädiq) sebagai metode transmisi ilmu pengetahuan dalam Islam. Selain itu, tulisan ini juga berupaya membuktikan bahwa khabar á¹£Ädiq merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
----------
1 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Historical Fact and Fiction, (Kuala Lumpur: UTM Press, 2011), hlm.xi
2 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hlm.121
3 Adi Setia “Epistemologi Islam Menurut al-Attas Satu Uraian Singkat†dalam ISLAMIA: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, Tahun II (Nomor.6, Juli-September 2005), hlm.54
4 Epistemologi berasal dari istilah Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Lihat, Nicholas Rescher, Epistemology: an Introduction to the Theory of Knowledge, (USA: State University of New York, 2003), hlm.xiii-xvii. Lihat juga, Ibrahim MadkÅ«r, Mu’jamu al-Falsafah, (Mesir: Hai’ah al-‘Ammah li al-Shu’ūn al-Maá¹ba’ al-AmÄ«rah, 1983), hlm.1. Lihat juga, Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Belukar, 2008), p.28
5 Adnin Armas, Krisis Epistemologi dan Islamisasi Ilmu, (Ponorogo: CIOS-ISID, 2007), hlm.1-2. lihat juga, Adian Husaini dkk., Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.7
6 Lihat, komentar Sa’ad al-Din al Taftazani, terhadap buku Najm al-Din al-Nasafi, dalam A Commentary on the Creed of Islam, translated and notes, Earl Edgar Elder, (New York: Columbia University, 1950), hlm.19
7 Teks asli berbunyi, “…the text which Uthman canonized was only one out of many rival texts, and we need to investigate what went before the canonical text.†Arthur Jeffery, Materials for the History of the Text of the Qur’an: the Old Codices, (Leiden: E.J. Brill, 1937), hlm.x
8 Teks asli berbunyi, “…the name of Mahomet was abused to support all possible lies and absurdities.†William Muir, The Life of Mahomet and the History of Islam to the Era of Hegira, Jilid 4 (London: t.p, 1861), hlm.1
9 Teks asli berbunyi, “It is difficult to regard the hadith literature as a whole as an accurate and trustworthy record of the sayings and doings of Muhammadâ€. Lihat Alfred Guillaume, The Traditions of Islam: An Introduction to the Study of Hadith Literature, (Oxford: Clarendon Press, 1924), hlm.12
10 Teks asli berbunyi, “We shall not meet any legal tradition from the Prophet which can be considered authentic†lihat Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, cetakan kedua, (Oxford: Clarendon Press, 1959), hlm.149
11 Aslinya berbunyi, “A great many traditions in the classical and other collections were put into circulation only after shafi’i’s time. The first considerable body of legal traditions from the Prophet originated toward the middle of the second century†Ibid, hlm.4
12 Aslinya berbunyi “Even the classical corpus contains a great many traditions which cannot possibly be authentic†Ibid, hlm.4
B. Sumber Kebenaran dalam Epistemologi Islam
Dalam Islam, kebenaran (ḥaq) dan realitas (ḥaqīqah) memiliki kedudukan yang penting. Keduanya adalah hal yang paling signifikan untuk memahami hubungan antara filsafat Islam dan sumber wahyu dalam Islam. Menurut Syeed Hossein Nasr, pada saat yang sama, al-ḥaqīqah merupakan kenyataan yang berasal dari al Qur'an.13 Artinya, kebenaran dan realitas dalam Islam adalah satu kesatuan utuh (tauhidi) yang tidak terpisah antara satu dengan lainya. Maka ,memisahkannya adalah sebuah kesalahan yang sudah semestinya tidak terjadi. Hans Deiber berkesimpulan bahwa cara pandang Islam tidak mengenal dikotomi dan permusuhan antara Islam dengan sains, antara wahyu dengan akal.14
Dilihat dari sumbernya, kebenaran dalam Islam dapat diraih melalui empat sumber.15 Pertama, persepsi indra (idrÄk al-ḥawÄss).16 Persepsi indra atau pancaindra terbagi menjadi dua, pancaindra eksternal dan pancaindra internal. Pancaindra eksternal terdiri dari indra peraba (touch), perasa (taste), pencium (smell), pendengaran (hearing), dan penglihatan (sight). Dari indra inilah manusia dapat mencium dan membedakan bau, membedakan warna, melihat indahnya dunia dan alam semesta, menyebutkan mana yang gelap dan mana yang terang, mampu merasakan manis, asin, pahit, kecut, hambar, juga mampu mendengar suara-suara di sekitarnya.
Begitu pentingnya kelima indra ini, Aristoteles sampai menyebutkan, “Barang siapa yang hilang darinya indra, maka telah hilanglah ilmu darinya.†17 Dalam hal ini, Imam al-Ghazali pun sependapat dengan Aristoteles, bahwa kelima indra tersebut tufīdu mabda' al-ilmi.18 Lebih jelasnya, ia mengilustrasikan tubuh manusia sebagai sebuah kerajaan. Akal memiliki peran sebagai raja lalu kelima indra tersebut adalah pasukannya.19 Sedangkan pancaindra internal terdiri dari indra bersama (common sense), representasi (the representative power), estimasi (estimative power), rekoleksi (retentive power or power of recollection), dan imajinasi (imaginative power).20
Al-Attas menjabarkan bahwa proses tahapan manusia memperoleh ilmu pengetahuan adalah melalui tahapan yang cukup panjang. Dimulai dari persepsi, abstraksi, dan diakhiri dengan inteleksi yang bersifat intuitif. Objek ilmu pengetahuan diawali dengan melalui tahap persepsi oleh pancaindra eksternal, kemudian disalurkan kepada pancaindra internal pertama, yaitu indra bersama (common sense). Indra bersama akan mengabstraksi bentuk dari objek ilmu tersebut menjadi sebuah gambaran (image) melalui proses yang disebut kemampuan representative (the representative power). Lalu, ketika objek ilmu hilang dari indra eksternal, gambaran objek tersebut ditangkap makna non-indrawinya oleh fakultas estimasi (estimative power), kemudian dibentuk putusan serta pendapat melalui jalan imajinatif seperti benar atau salah, baik atau buruk, dst. Makna non-indrawi tersebut akan direkam dan disimpan oleh fakultas rekolektif (retentive power or power of recollection) hingga sampai pada fakultas imajinasi.21
Fakultas imajinasi bertugas memadukan dan memisahkan makna-makna partikular yang telah tersimpan oleh fakultas rekolektif yang didasari oleh rasio praktis maupun rasio teoritis. Fakultas ini memiliki dua aspek, yaitu sebagai sensitif dari bentuk-bentuk indrawi, juga sebagai penerima rasional dari bentuk-bentuk yang tampak.22 Proses tahapan ini menunjukkan bahwa persepsi Indra (idrÄk al-ḥawÄss) atau al-ḥawÄssul al-khamsah memberikan sumber informasi dan juga sumber ilmu kepada manusia. Hal yang serupa juga telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an:
Ø£ÙŽÙَلَمْ يَسÙيرÙوا ÙÙÙŠ الأرْض٠ÙَتَكÙونَ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ Ù‚ÙÙ„Ùوبٌ يَعْقÙÙ„Ùونَ بÙهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعÙونَ بÙهَا ÙÙŽØ¥Ùنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَار٠وَلَكÙنْ تَعْمَى الْقÙÙ„Ùوب٠الَّتÙÙŠ ÙÙÙŠ الصّÙدÙورÙ23]
“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.â€
Di sini, tampak jelas bahwa epistemologi Islam sama sekali tidak menolak pancaindra sebagai sumber ilmu. Sebaliknya, ia merupakan perwujudan dari sebuah pintu dalam sepetak rumah bernama pengetahuan manusia secara komplit. Dari situlah sebetulnya pengetahuan manusia bermula dan berawal.
Kedua, proses akal sehat (ta’aqul). Selain pancaindra yang telah dijabarkan sebelumnya, Islam juga menempatkan akal sehat sebagai sarana mendapatkan ilmu pengetahuan. Akal sehat menjadi faktor pembeda antara manusia dengan hewan.24 Ia juga berfungsi menutupi kelemahan dan hal-hal yang tidak mampu dilakukan panca indra. Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa akal lebih patut disebut "cahaya" ketimbang indra.25 Akal mampu menangkap objek sesuai dengan realitas yang ada, seperti cermin yang selalu menampakkan sesuatu sebagaimana mestinya.26 Di sini tampak bahwa akal berperan menjelaskan sebuah realitas kepada bentuk aslinya, bukan hanya sebagaimana yang terlihat dan tampak.
Selain itu, akal fikiran manusia juga dapat mengatur serta menemukan hubungan-hubungan yang sesuai dalam setiap wilayah ilmu pengetahuan, antara satu dengan yang lainya.27 Sebagai contoh, ketika indra mata melihat bulan, maka yang terlihat adalah bulan yang mempunyai diameter kecil, sekecil koin logam. Padahal sejatinya, bulan memiliki ukuran yang jauh lebih besar, tidak sekecil koin.28 Walaupun belum pernah ke bulan sekalipun, manusia akan menolak bahwa bulan itu kecil. Otak manusia tidak akan mau menerimanya.
Sedangkan menurut al-FarÄbi, akal bekerja sebagai kekuatan gerak berfikir manusia untuk memahami sebuah objek, untuk dikembangkan menjadi ilmu-imu dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya seni dan industri (sina’Ät).29 Oleh sebab itu, al-FarÄbi menyebutkan bahwa dimensi akal tidak mungkin ditinggalkan, lebih-lebih dalam basis keilmuan manusia.
Lebih lanjut, akal juga memiliki kemampuan bertanya secara kritis tentang segala hal. Misalnya, bertanya tentang sebuah kejadian atau peristiwa: kapan terjadinya, apa kejadiannya, oleh siapa, dengan apa dan lain sebagainya. Dengan kata lain, akal bukan hanya sebuah rasio, ia adalah fakultas mental yang mampu mensistematiskan dan menafsirkan fakta-fakta empiris menurut kerangka logika, yang pada akhirnya memungkinkan pengalaman menjadi sesuatu yang dapat dipahami, serta memberi informasi baru, tatkala pengalaman yang bersifat empiris tidak dapat menerimanya secara valid. Maka, dapat disimpulkan bahwa akal lah yang menutupi kelemahan kerja pancaindra yang masih amat terbatas.30 Singkatnya, akal sebagai sumber ilmu menyempurnakan kerja manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara utuh, sehingga menjadi sesuatu yang dapat diketahui dan dipahami secara benar.31
Yang ketiga adalah intuisi kalbu. Selain akal, hal lain yang tidak kalah penting adalah intuisi. Di dalam Islam, intuisi juga menjadi salah satu gerbang diterimanya sebuah ilmu dan kebenaran. Menurut seorang cendekiawan berkebangsaan Pakistan, Sir Muhammad Iqbal, intuisi menjadi pengalaman unik yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari alam fikiran. Maka, ia pun yang menghasilkan pengetahuan tertinggi.32 Bukan hanya Iqbal, al-Attas pun berpendapat serupa, bahwa intuisi memiliki peran sebagai salah satu elemen mendasar dalam pencarian kebenaran.33 Dengan intuisi kalbu, manusia mampu menangkap pesan-pesan gaib, isyarat-isyarat Tuhan, serta menerima ilham, fath, kasb,34 dan lain sebagainya. Contohnya, ketika seseorang dapat percaya tanpa harus berfikir panjang mengenai siapa orang yang ada di hadapannya dan dari mana asalnya, lalu secara seketika menyimpulkan bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak sedang menipu. Di sini, intuisi memiliki peran dalam menilai sesuatu. Selain itu, intuisi sebagai sumber pengetahuan bukanlah hasil dari fikiran sadar atau persepsi langsung,35 namun merupakan respon langsung dari iman dan respon total dari sebuah situasi.
Lebih dalam lagi, al-Attas meneruskan bahwa meskipun pengetahuan intuitif tidak dapat dikomunikasikan, namun pemahaman mengenai kandungannya atau ilmu pengetahuan yang berasal darinya bisa ditransformasikan. Ia membagi intuisi menjadi berbagai jenis dan tingkatan, intuisi yang terendah dialami oleh ilmuwan dan sarjana dalam penemuan-penemuan mereka, sedangkan yang tertinggi dialami oleh para Nabi, wali dan orang-orang soleh.36 Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa intuisi merupakan pengenalan langsung dan cepat terhadap kebenaran religius, yaitu berupa realitas dan eksistensi Tuhan. Pengenalan tersebut diperoleh melalui intuisi tingkat tinggi yang disebut intuisi akan eksistensi (intuition of existence). Oleh sebab itu, al-Attas meyakini bahwa intuisi adalah pekerjaan hati (qalb).37 Selain itu, al-Attas menekankan bahwa proses persepsi dan inteleksi yang bersifat intuitif memiliki kedudukan yang kuat, sehingga kedua hal tersebut menegaskan bahwa proses memperoleh ilmu pengetahuan adalah aktivitas spiritual.
Selaras dengan itu, Alparslan Acikgenc menyebutkan bahwa tugas qalb sebagai pusat pengalaman wahyu adalah memproyeksikan kebenaran yang tak terlihat atau gaib. Ia pun menguraikan arti qalb dalam surat al-Qaf ayat 3738 sebagai fakultas pengalaman atau “faculty of experienceâ€. Menurutnya, hal ini disebabkan pada kenyataan apa yang dirasakan qalb berlawanan dengan apa yang didengar sebagai sebuah fakultas pengalaman indrawi. Oleh sebab itulah Allah berfirman dalam al-Qur’an “QulÅ«bun ya’qilÅ«na bihÄâ€. 39
“Heart is implied as the center of experience while the revelation projects the unseen truth, namely the truth of gaib. We can interpret qalb in this verse as a faculty of experience, because it is contrasted with ear, a faculty of sense-experience. In fact, we see that in the same manner, (heart) is contrasted with other faculties of experience.â€40
Dalam hal ini, Imam al-Ghazali merumuskan bahwa intuisi terbagi menjadi dua, intuisi pertama didapat tanpa pelatihan apapun atau tanpa kesengajaan. Sedangkan intuisi yang kedua adalah intuisi yang dapat dilatih untuk mendapakannya. Seperti sebuah inspirasi ilahi yang datang dalam bentuk mukasyafah bagi para ulama’ dan hukama’. Oleh sebab itu, al-Ghazali menjelaskannya dengan terminologi berbeda mengenai intuisi kalbu ini. Yang pertama untuk hal-hal yang lembut, sedangkan yang kedua untuk hal-hal yang nyata.41 Maka tak salah bila Iqbal menyebut intuisi kalbu ini sebagai sarana mengenal dirinya serta mengenal lebih jauh mengenai sesuatu yang ada di luar dirinya yang bermuara pada pengalaman intuisi mengenai Allah SWT.42 Hal ini pun selaras dengan hadist Nabi “man ‘arafa nafsahu faqod ‘arafa rabbahâ€.43
Sumber terakhir adalah informasi yang benar (khabar á¹£Ädiq).44 Ia merupakan sumber kebenaran yang tak kalah penting dalam Islam. Dalam bahasa inggris, khabar á¹£Ädiq sering disebut dengan "true report"45 atau "true narrative".46 Sumber kebenaran yang berasal dari khabar á¹£Ädiq bersandar kepada otoritas yang diterima dan diteruskan (ruwiya wa nuqila) hingga akhir zaman. Sumber utamanya adalah wahyu, baik kalam Allah maupun sunnah Rasulullah.47 Untuk lebih jelasnya, sumber kebenaran keempat ini akan dijabarkan lebih luas pada sub bab berikutnya.
----------
13 Dalam hal ini, al-Attas memiliki pendapat yang sama, bahwa seluruh ilmu dalam islam dikembangkan melalui al-Qur’an. Lihat, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and the Secularism, (Kuala Lumpur: IBFIM, 2014), hlm.143. lihat juga, Syeed Hossein Nasr (ed), Encyclopedia of Islamic Philosophy, part I, (Lahore Pakistan: Suhail Academy, 2002) hlm.29
14 Hans Daiber, “The Way from God’s Wisdom to Science in Islam: Modern Discussions and Historical Background,†dalam Islamic Science and the Contemporary World: Islamic Science in Contemporary Educations, (ed) Baharudin Ahmad, (Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, 2008), hlm.8
15 Ada pula yang menyebutkan bahwa sumber Ilmu pengetahuan terdiri dari tiga sumber, salah satunya adalah ImÄm al-Nasafi. Beliau mengatakan, “wa asbÄbul ilmi thalÄthatun, al-ḥawÄss al-khamsah, al-‘aql al-SalÄ«m, al-khabar á¹£Ädiq†yang berarti, â€Maka segala perkara yang menghasilkan ilmu bagi maqulat itu tiga perkara: suatu panca indera yang lima, kedua khabar sadiq (yakni berita yang benar), ketiga ‘aqal.†lihat; Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of the ‘AqÄ’id of al-Nasafi, (Kuala Lumpur: Department of Publications University of Malaya, 1988), hlm.53. Baca juga Wan Mohd Nor Wan Daud, “Beberapa Aspek Pandang Alam Orang Melayu dalam Manuskrip Melayu Tertua al-Aqa’id al-Nasafi†dalam Afkar: Journal of ‘Aqidah and Islamic Thought, Bil.6, (Kuala Lumpur: University of Malaya, Mei 2005), hlm.8
16 Lihat juga, Adi Setia “Epistemologi Islam Menurut al-Attas Satu Uraian Singkat†dalam ISLAMIA: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, Tahun II (Nomor.6, Juli-September 2005), hlm.54
17 Ayatullah Murtadha Muthahhari, Pengantar Epistemologi Islam, trj: M. Jawad Bafaqih, (Jakarta: Shadra Press, 2010), hlm. 38
18 Imam Ghazali, MizÄn al-‘Amal. Diedit oleh SulaymÄn Slaim al-BawwÄb, (Damascus: DÄr al-Ḥikmah, 1986), hlm. 26. Lihat juga, Mohd Zaidi Ismail, The Sources of Knowledge in al-Ghazali’s Thought: a Psycological Framework of Epistemology, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2002), hlm.13
19 Imam Ghazali, IhyĒ Ulūm al Dīn, vol. 2, hlm. 10
20 Hamid Fahmy Zarkasyi, al-Ghazali’s Concept of Causality: with Reference to His Interpretations of Reality and Knowledge, (Kuala Lumpur: IIUM, 2010), hlm.163
21 Dalam pandangan Chittick, Ibn ‘Arabi menyebut “nalar†(‘aql) sebagai fakultas untuk memahami bahwa Tuhan itu jauh, sedangkan “imajinasi†(khayÄl) sebagai fakultas untuk melihat Tuhan itu dekat. Lihat, William C. Chittick, Kosmologi Islam dan Dunia Modern: Relevansi Ilmu-Ilmu Intelektualisme Islam, terj Arif Mulyani, cetakan pertama, (Mizan: Bandung, 2007), hlm.93
22 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hlm. 151-155. Lihat juga, Hamid Fahmy Zarkasyi, al-Ghazali’s Concept of Causality: with Reference to His Interpretations of Reality and Knowledge,( Kuala Lumpur: IIUM, 2010), p.168-170
23 QS al-ḤÄjj: 46 lihat juga, QS al-QÄf:37, QS al-A’rÄf:179, QS ‘Ali ‘ImrÄn:138 dan QS al-Maidah:15
24 Para filsuf, semisal al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan al-Ghazali menyebutkan bahwa sebenarnya binatang pun memiliki akal dan daya khayal, akan tetapi terdapat perbedaan antara apa yang dimiliki manusia dengan apa yang dipunyai hewan. Akal versi manusia memiliki kedudukan lebih tinggi dan mulia sebab akal tersebut digunakan untuk meraih kemuliaan di dunia maupun akhirat. Sedangkan pada hewan, akal hanya digunakan sebagai alat untuk mencari makan atau untuk melindungi dirinya. Lihat; al-Farabi, Fuṣūṣ al-ḤikÄm, Tahqiq: Muhammad HasÄn ‘Ali YasÄ«n, (BaghdÄd: DÄr al-Ma’Ärif, 1976), hlm.78-79. Bandingkan dengan, Ibn Sina, AḥwÄl, al-Nafs: RisÄlah fi al-Nafs wa al-BaqÄ’ihÄ wa al- Ma’ÄdihÄ, tahqiq: Ahmad Fuad AhwÄni, (Paris: Dar Babylon, 2007), hlm.58-62. Ibn Rusyd, Talḥis KitÄb al-Nafs, tahqiq: Ahmad Fuad AhwÄni, (Kairo: Maktabah al-Nahá¸ah al-Mishriyah, 1950), hlm.60, juga al-Ghazali, al-Munqidz min al-ḌalÄl, Tahqiq: JamÄ«l Shaliban, (Beirut: DÄr al-Andalus, 2003), hlm.84
25 Mulyadhi Kartanegara, Menyibak Tirani Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam, (Bandung: Mizan, 2005), hlm.21
26 Imam Ghazali, Mi’yÄr Ilmi, tahqiq: SulaimÄn Dunya, (Kairo: DÄr al-Ma’Ärif, 1960), hlm. 59
27 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.159
28 Imam Ghazali, MisykÄt… hlm. 33
29 Al-Farabi, ArÄ’ al-MadÄ«nah al-Faá¸Ä«lah, TahqÄ«q: Albert Nashri Nadir, (Beirut: DÄr al-Mashriq, 1973), p.67
30 Dalam hal ini al-Attas menambahkan kata sifat “sehat†dalam terma akal (menjadi akal sehat), sebab bukan saja dikarenakan fikiran manusia sering tidak betul dan berangkat dari sebuah premis yang salah atau kesimpulan yang keliru meskipun berdasarkan premis yang betul, namun manusia juga sering terpengaruh oleh estimasi dan imajinasi, yang bisa saja salah ketika akal menegasikan kemampuan untuk memahami realitas spiritual melalui intuisi. Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas…, hlm.159
31 Bagaimanapun sempurnanya akal, ia masih memiliki kemampuan terbatas. untuk mengetahui ruh misalnya, akal tidak mampu sampai kepada ruh tersebut. Dikarenakan keterbatasan inilah, Allah SWT mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada Manusia. Lihat, Ismail Fajrie Alatas, Sungai Tak Bermuara Risalah Konsep Ilmu Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Insani, (Jakarta: Diwan, 2006), hlm. 150
32 Allama Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, tanpa tahun dan penerbit, pdf, hlm.10
33 Ibid, hlm. 160
34 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme…. hlm. 206
35 Harold H. Titus, Persoalan-Persoalan Filsafat, Terj, H. M. Rosjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 203-204
36 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam….. hlm. 160
37 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam…., hlm. 119
38 Ø¥Ùنَّ ÙÙÙŠ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ Ù„ÙŽØ°Ùكْرَى Ù„Ùمَنْ كَانَ لَه٠قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ÙˆÙŽÙ‡ÙÙˆÙŽ Ø´ÙŽÙ‡Ùيدٌ
Artinya: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikannya.
39 Ø£ÙŽÙَلَمْ يَسÙيرÙوا ÙÙÙŠ الأرْض٠ÙَتَكÙونَ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ Ù‚ÙÙ„Ùوبٌ يَعْقÙÙ„Ùونَ بÙهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعÙونَ بÙهَا ÙÙŽØ¥Ùنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَار٠وَلَكÙنْ تَعْمَى الْقÙÙ„Ùوب٠الَّتÙÙŠ ÙÙÙŠ الصّÙدÙور٠(QS al-HÄjj : 46)
40 Alparslan Acikgenc, Islamic Science: Toward a Definition, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), hlm. 47
41 Imam Ghazali, KimiyÄ’ Sa’Ädah in Majmū’u RasÄil al-Ghazali.... hlm. 135-139
42 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam.... hlm. 160
43 Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan perkataan “diri†bukanlah dalam artian fisik, melainkan diri dalam konteks spiritual yang mengenal serta mengakui Tuhan sebagai penciptanya. Lihat, Allama Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, tanpa tahun dan penerbit, pdf, hlm. 17-26. Lihat juga, Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam.... hlm. 160 dan QS al-A’Raf: 172
44 Dalam istilah lain, khabar ṣadiq juga dapat disebut sebagai “otoritas.†Lihat, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dan Filsafat Sains, terj: Saiful Muzani, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 39
45 Lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam…., hlm. 14
46 Lihat, penjelasan Sa’ad al-Dīn al-Taftazani, dalam A Commentary on the Creed of Islam, translated and notes by: Earl Edgar Elder, (Columbia University: New York, 1950), hlm. 19. lihat juga, Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.205
47 Ibid, hlm.206
C. Pengertian Khabar á¹¢Ädiq dalam Epistemologi Islam
Bila ditelaah lebih dalam, khabar secara etimologi berarti berita (al-nabĒ)48 dan sekumpulan dari berita-berita atau kabar-kabar.49 Khabar bermakna pula, cerita, riwayat, pernyataan, ucapan (talfana lī, kallama, rasala)50 atau to contact, communicate with. Ibnu Taimiyyah mendefinisikan khabar dengan lebih rinci yakni sebuah berita atau kabar; baik yang benar maupun yang keliru atau bohong.51 Secara terminologi, khabar berarti berita yang mengabarkan tentang sesuatu kejadian, yang ditransfer dan dibicarakan melalui perkataan, tulisan atau gambaran dari kejadian-kejadian yang baru.52 Ada pula yang menyebut bahwa khabar secara bahasa memiliki makna sama dengan hadist, yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada seseorang. Namun, hadist memiliki makna yang lebih umum dari khabar, sehingga tiap hadist bisa disebut sebagai khabar, tapi tidak semua khabar dapat disebut hadist.53
Sedangkan á¹£Ädiq secara etimologi berarti benar “ghairu kadzÄ«b†atau “ṣarikh†(true truthful).54 Dilihat dari makna terminologisnya, á¹£Ädiq55 berarti suatu fakta yang sesuai dengan realita. Lawan katanya adalah bohong (kadzb). Pelakunya disebut “ṣÄdiqun†(true man). Orangnya disebut “siddÄ«q†(man of truth).56 Kebalikannya disebut dengan berita palsu (khabar kÄdzib). Menurut al-Attas, khabar á¹£Ädiq atau berita yang benar haruslah didasari oleh sifat-sifat dasar saintifik atau agama, yang diriwayatkan oleh otoritas agama yang otentik. Artinya, khabar benar-benar diriwayatkan oleh ulama yang memiliki otoritas dalam bidang agama, bukan diriwayatkan oleh sembarang orang. Dalam bukunya ia berpendapat:
“Islam affirms the possibility of knowledge; that knowledge of realities of things and their ultimate nature can be established with certainty by means of our external internal sense and faculties, reason and intuition, and the true report of scientific or religion nature, transmitted by their authentic authorities.†57
D. Pembagian dan Validitas Khabar á¹¢Ädiq
Al-Shawkani memilah khabar menjadi tiga jenis. Pertama, khabar yang sudah pasti benar (al-maqthu’ bi á¹£idqihi), baik yang kebenarannya bernilai pasti dan mutlak, yang bersumber dari khabar mutawatir dan pengetahuan apriori (awwaliyÄt), maupun yang diyakini benar setelah dilakukannya penelitian serta dibuktikan dan diuji secara ilmiah. Bila merujuk kepada yang sudah pasti benar, al-Qur’an memiliki derajat tertinggi, setelahnya adalah hadist Rasulullah SAW, dan keduanya diterima secara universal.58 Kedua, khabar yang palsu, keliru atau dusta (al-maqthu’ bi kidzbihi). Hal ini berlaku pada segala hal yang diketahui salahnya secara pasti dan langsung ataupun yang diketahui dengan cara pembuktian. Ketiga, khabar yang tidak dapat dipastikan benar atau salahnya (mÄ lÄ yuqtha’ bi á¹£idqihi wa lÄ kidzbihi), yaitu khabar yang sumbernya sama sekali tidak diketahui atau sumbernya tidak jelas, termasuk di dalamnya khabar yang belum tentu atau ada kemungkinan benar tapi kedudukannya belum pasti, maupun sebaliknya yaitu, khabar yang kemungkinan salah, palsu atau keliru, walaupun belum pasti demikian.59
Bila dilihat dari otoritasnya, khabar á¹£Ädiq terbagi menjadi dua. Pertama, otoritas mutlak (absolute authority) yang terdiri dari, otoritas ketuhanan yaitu al-Qur’an dan otoritas kenabian, yaitu hadist Rasulullah. Kedua, otoritas nisbi (relative authority) yang terdiri dari kesepakatan alim ulama (tawÄtur) dan khabar yang berasal dari orang terpecaya secara umum.60 Khabar ini kemudian diperjelas lagi dengan dua kriteria. Pertama, lidzÄtihi atau binafsihi yang berarti berita benar ini benar dengan sendirinya tanpa diperkuat oleh sumber lain. Sedangkan kedua, bi ghairihi, yakni berita benar yang masih didukung dan diperkuat oleh sumber yang lain,61 yang mana akal kita akan menolak bahwa mereka bersekongkol untuk berdusta. Sehingga secara umum khabar á¹£Ädiq dapat dipahami sebagai sebuah berita benar, yang mengabarkan tentang segala sesuatu, dibicarakan melalui perkataan, tulisan maupun gambaran yang disampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain.
Merujuk dari argumentasi di atas, al-Qur’an menepati kedudukan tertinggi dalam sumber kebenaran. Ia bersifat qaá¹â€™i al-thubÅ«t wa qaá¹â€™i al-dalÄlah62 yaitu dari makna maupun maksudnya telah jelas autentisitasnya. Ia juga bersifat thabit tetap secara qaá¹â€™i, sebab telah diakui, dibuktikan serta dipastikan ke-tawatur-annya oleh seluruh umat manusia dan tidak terdapat perbedaan sedikitpun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an turun dalam rentang waktu 23 tahun, diturunkan dalam satu malam ke langit terbawah (baÄ«t izzah), yang kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap63 kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril, dan disampaikan pada sahabat dari generasi ke generasi melalui mata rantai (talaqqy-mushÄfahah) tradisi lisan yang jelas.64 Dalam penyampaiannya Nabi Muhammad menghafalnya, namun secara bergantian beliau membaca al-Qur’an bersama Malaikat Jibril. Untuk menjaga hafalan Rasulullah, Malaikat Jibril mengunjunginya setiap tahun untuk memantapkan hafalannya.65 Setelah dihafal, Rasulullah menyampaikan al-Qur’an dengan cara diajarkan serta dijelaskan kepada para sahabat. Ini terlihat begitu Nabi sampai di Madinah, beliau membuat sebuah kelompok belajar (suffah) di dalam masjid.66 Nabi juga menyediakan makanan dan tempat tinggal.67 Dengan kata lain, tradisi pengkajian al-Qur’an begitu sistematis sedemikian rupa lewat kelompok-kelompok belajar, yang sudah terjadi secara turun-temurun. Selain itu, al-Qur’an tidak hanya berupa sebuah naskah teks tertulis (rasm), ia juga merupakan bacaan (qirÄ’ah) yang dihafalkan, sehingga al-Qur’an dapat terus dijaga.
Setelah disampaikan kepada para sahabat, al-Qur’an pun dicatat dan ditulis oleh kurang lebih 65 sahabat Rasulullah, yang berperan sebagai penulis wahyu.68 Selain menulis, para sahabat juga menghafalnya. Dua hal ini secara langsung diawasi oleh Rasulullah SAW secara rutin. Biasanya Nabi memanggil para penulis untuk menulis ayat al-Qur’an setiap kali ayat al-Qur’an turun. Setelah selesai, para sahabat membaca ulang di hadapan beliau agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Setelah Rasulullah wafat, tradisi ini terus berlanjut hingga pada zaman Abu Bakar diputuskan untuk dikumpulkan menjadi satu kitab utuh, disebabkan banyak huffaẓ (penghafal al-Qur’an) yang meninggal dalam peperangan Yamama. Perlu dicatat, bahwa al-Qur’an telah ditulis secara utuh sejak zaman Nabi Muhammad, hanya saja belum disatukan menjadi satu dan surah-surah yang ada pun belum tersusun.69 Penyusunan al-Quran tidak dilakukan sembarangan, sahabat diharapkan menyerahkan catatan sekaligus menyetor hafalan mereka diiringi dua saksi yang mendampingi. Ia juga diharuskan bersumpah bahwa telah mendapatkan langsung dari Rasulullah SAW.70
Dalam proses ini, penunjukan Zaid bin ThÄbit sebagai ketua pengumpul al-Qur’an bukan tanpa alasan. Sejak usia dua puluhan ia sudah tinggal bersama Rasulullah dan bertindak sebagai “kuttÄb al-wahyi†atau penulis wahyu yang amat cemerlang, sehingga Abu Bakr as-Siddiq memberikan kualifikasi kepada Zaid. Pertama, pada masa mudanya Zaid terkenal dengan kekuatan energinya serta menunjukkan vitalitas yang luar biasa. Kedua, akhlaknya tidak pernah tercemar dengan perbuatan yang buruk. Ketiga, Zaid memiliki kompetensi serta kecerdasan yang tinggi. Keempat, ia memiliki pengalaman sebagai penulis wahyu. Kelima, ia adalah salah satu sahabat yang sempat mendengar bacaan al-Qur’an Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad secara langsung.71 Keenam, Zaid bukan seorang sahabat yang bersifat fanatik dan sangat mudah mendengarkan pendapat orang lain.72 Ketujuh, Zaid juga menguasai dan belajar berbagai bahasa.73 Artinya, penunjukkan Zaid bin Thabit bukan secara kebetulan. Semua telah diperhitungkan begitu matang. Ini menunjukkan bahwa al-Qur’an bersumber dari khabar á¹£Ädiq yang terjaga kebenarannya bahkan dijamin sendiri oleh Allah SWT sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, “innÄ nahnu nazzalnÄ al-dzikra wa innÄ lahÅ« laḥÄfiẓūnâ€. 74
Tidak berbeda dari al-Qur’an, sumber periwayatan hadist pun tergolong dalam khabar á¹£Ädiq yang dapat dipertanggungjawabkan autentisitasnya. Ia juga berperan sebagai tafsir dan penjelas al-Qur’an yang paling otentik.75 Di dalam ilmu hadist terdapat empat syarat dan kriteria bagaimana sebuah khabar masuk pada tataran khabar mutawÄtir. Syarat pertama adalah diriwayatkan oleh rawi-rawi dalam jumlah yang banyak secara berturut-turut.76 Ini berarti khabar tersebut haruslah diriwayatkan secara orang perorangan dengan jumlah yang banyak secara beruntun, estafet, tanpa terputus. Yang kedua, periwayatan yang banyak dan berturut-turut ini terdapat dalam setiap tingkatan sanad. Artinya, tidak hanya diriwayatkan secara berturut-turut, namun perawinya pun harus merata, ada di setiap generasi.
Syarat selanjutnya, perawi yang meriwayatkan harus terpercaya serta terbebas dari kebohongan.77 Dengan kata lain, diriwayatkan secara terus-menerus tanpa terputus, perawinya berasal dari beberapa tingkatan sanad, dengan perawi yang terpercaya dan terbebas dari kebohongan. Sedangkan yang terakhir adalah, perawi harus menjadikan panca indra sebagai landasan periwayatannya.78 Artinya, ia pernah melihat, menyaksikan, mengalami, atau mendengar kabar tersebut secara langsung, tidak menerka-nerka “al-MushÄhadah wa al-samÄ’ lÄ â€˜alÄ sabÄ«l al-ghalaá¹â€, tanpa disertai ilusi ataupun praduga.79 Maka tidak mengherankan bila khabar mutawÄtir tidak diragukan kebenarannya, mengingat begitu ketatnya kriteria sebuah khabar hingga dapat diterima menjadi sumber yang benar-benar mutawÄtir.
Bila pada hadist yang derajatnya mutawÄtir para ulama menetapkan persyaratan yang begitu ketat, maka demikian juga dengan khabar aḥad atau hadist aḥad. Menurut Syamsuddin Arif, khabar aḥad pun harus diklasifikasi kualitas sumbernya: siapa yang meriwayatkan, siapa yang menyampaikan dan yang mengatakannya, serta kualifikasi dan otoritas atas sanad dan isnadnya. Artinya, tidak sembarangan dan semena-mena.80 Persyaratan yang begitu ketat ini tidak hanya berlaku pada narasumber atau perawinya, namun juga isi pesan (matan) beserta penyampaiannya. Dengan kata lain, khabar aḥad tidak serta merta ditolak ataupun diterima, tapi harus melalui proses panjang hingga pada akhirnya dapat diterima sebagai khabar benar.
As-Shawkani menegaskan, sebuah khabar ahad baru dapat diterima sebagai sumber kebenaran bila memenuhi beberapa syarat. Pertama, sumber berita/khabar harus berasal dari seseorang yang “mukallaf†dalam artian orang tersebut telah terkena kewajiban melaksanakan perintah agama serta mampu mempertanggung jawabkannya. Oleh sebab itu, hanya orang “balÄ«gh†cukup umur saja yang beritanya dapat diterima, sedang anak kecil dan orang gila tidak diterima khabar-nya. Kedua, sumber khabar harus berasal dari yang beragama Islam. Hal ini kembali ditegaskan oleh Imam Ibn HibbÄn (354H - 965M) bahwa orang yang secara dzahir seorang Muslim namun batinnya kafir “zindÄ«qâ€, misalnya sophis, agnostik, skeptis, relativis bahkan atheis, meskipun mereka mengaku-ngaku diri sebagai ulama, tetapi jauh di dalam fikiran mereka sengaja ingin menimbulkan keragu-raguan (li yuqī’u al-shÄkk wa al-rayb) pada masyarakat serta menyesatkan orang lain, khabarnya tidak dapat diterima.81 Maka kabar, cerita, ataupun pernyataan yang berasal dari seorang nasrani atau kafir, dalam hal ajaran Islam sedikitpun tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, al-Attas menekankan untuk tidak mudah menerima kabar-kabar dan informasi yang datang dari orientalis, sebab mereka termasuk kaum Nasrani, yang kabarnya berkenaan dengan agama perlu dipertanyakan kebenarannya. Dalam bukunya al-Attas menyebutkan:
“We must question the way they arrive at their theories, their way of reasoning and analysis, their setting forth of premises and arrival at conclutions, their raising of problems and arrival at their solutions, their understanding of recondite matters of meaning, their raising of doubts and ambiguities and their insistence upon empirical fact.â€82
Ketiga, perawi haruslah seorang yang memiliki intergritas moral yang tinggi (‘adÄlah), sehingga menunjukkan bahwa ia orang yang dapat dipercaya karena kerwibawaannya (murū’ah), ketaqwaannya dan jauh dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Ini berarti, orang yang fasiq khabar-nya tidak dapat diterima, sebab ia bukan termasuk lagi dalam golongan orang yang adil (‘adÄlah).83 Sedangkan yang keempat, al-AshawkÄni menjelaskan bahwa perawi haruslah seorang yang “á¸abá¹â€ atau memiliki ketelitian serta kecermatan. Ibn HibbÄn memasukkan di dalamnya bahwa orang yang tidak teliti, orang yang bukan pakar atau ahli dalam bidangnya,84 atau berasal dari orang yang tidak memiliki otoritas sebagai kabar yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini Imam Malik pun sependapat, bahwa orang bodoh yang sudah dikenal kebodohannya, maka ucapannya tidak perlu dicatat.85
Kelima, seorang perawi haruslah terbebas dari sifat “mudallis†yakni tidak menyembunyikan sumber kabar serta senantiasa berkata jujur dan berterus terang. Dengan kata lain, perawi yang memiliki kepribadian suka berbohong,86 walaupun sedikit, secara prosedural tidak dapat diterima khabarnya. Mudahnya, di dalam epistemologi Islam kebenaran bisa didapat atau diraih dengan menggunakan khabar/berita. Namun, bukan sembarang khabar yang dapat diterima, tetapi hanya “khabar á¹£Ädiq†berita benar, yang benar-benar terverifikasi serta teruji validitasnya dengan kriteria yang begitu ketat.
Khabar selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan derajat validitasnya serta sifat yang mengikatnya menjadi: qhaá¹â€™i yakni yang bersifat pasti, jelas atau gamblang dan ẓanni yang berupa kemungkinan atau dugaan. Kemudian masing-masingnya terbagi lagi berdasarkan kebenaran sumbernya (tsubÅ«t) dan maksud implikasinya (dalÄlah). Dengan kriteria ini, khabar dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan.87 Pertama, qaá¹â€™i al-thubÅ«t wa qaá¹â€™i dalÄlah, yaitu khabar yang orisinil dan sudah jelas otentisitasnya, tidak diragukan serta dipersoalkan kebenaran sumbernya dari segi maksud maupun maknanya. Contohnya, ayat-ayat al-Qur’an dan hadist mutawatir88 yang bersifat muhkamÄt, baik yang membicarakan masalah hukum maupun keimanan.
Kedua, qaá¹â€™i al-thubÅ«t ẓannÄ« al-dalÄlah yaitu khabar yang yang telah dibuktikan keasliannya serta kebenaran sumbernya akan tetapi belum diketahui secara pasti makna ataupun maksud yang terkandung di dalamnya. Misalnya, ayat-ayat al-Qur’an yang mutasyabihat berbicara mengenai hal-hal yang samar, ataupun khabar mutawatir yang memiliki makna dua atau lebih.89 Ketiga, ẓanni al-thubÅ«t wa ẓanni al-dalÄlah90 yaitu khabar yang kebenaran sumber, otensititas, serta maksud dan maknanya masih diperdebatkan. Contohnya, semua khabar ilmu selain yang disebutkan di atas, seperti hadist ahad ataupun khabar secara umum.91
Dengan kata lain, secara epistemologis, al-Qur’an dan hadist baik yang mutawatir maupun yang aḥad bersifat mengikat, sehingga validitasnya memiliki otoritas yang begitu tinggi. Namun, di lain sisi, meskipun memiliki validitas yang tinggi, manusia masih diberikan kebebasan untuk berijtihad—tentu hanya untuk manusia yang memiliki kapabilitas untuk berijtihad dan bukan sembarang orang—bila hal itu tekait dengan ayat al-Qur’an atau hadist yang bersifat umum dan memiliki arti yang dapat diperdebatkan. Oleh sebab itu, perlu pula ditelaah lebih dalam mengenai kedudukannya, bersifat qaá¹â€™i ataukah ẓanni.
----------
48 Muhammad Abu Laith Khairu ‘Abadi, ‘UlÅ«mul HadÄ«th Äá¹£iluhÄ wa mu’aá¹£iluhÄ, (Malaysia: Darul ShÄkir, 2011), hlm. 26-27
49 Abu ‘AbdurrahmÄn al-KhalÄ«l Ibnu Ahmad, KitÄbu al-‘Aini, Jilid 8 (DÄr al-Maktabah al-HilÄl, t.t), hlm. 258
50 Rahi BaalbÄki, al-Maurid, Edisi ke 7, (BeirÅ«t Lebanon: DÄr al-Ilm limabyin, 1995), hlm. 498
51 Ibnu Taymiyyah, ‘Ilmu al-HadÄ«th, (Lebanon: DÄr al-KutÅ«b al-‘Alamiyyah, 1985), hlm. 36
52 Ahmad Mukhtar ‘Abdul HamÄ«d ‘Umar, Mu’jamu al-LughÄh al-‘Arabiyyah al-Mu’aá¹£irah, Jilid 1, Cetakan Pertama (‘AlÄ«m al-KitÄb, t.t), hlm. 608
53 Ibid, hlm.15
54 Rahi Baalbaki, al-Maurid, …. , hlm. 684
55 “Ṣadiq†berakar dari kata “al-á¹¢Ädiqâ€, yang merupakan salah satu dari nama Allah SWT. Lihat, Ahmad Mukhtar ‘Abdul Hamid Umar, Mu’jamu al-LughÄh al ‘Arabiyyah al-Mu’Äá¹£irah, Jilid 2…, hlm. 1283
56 Ali Muhammad al Khuli, a Dictonary of Islamic Terms, tanpa tahun, pdf, hlm. 63-64
57 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam…., hlm. 14. lihat juga Dinar Dewi Kania, Epistemologi Syed Muhammad Naquib al-Attas, makalah, hlm. 4
58 Adian Husaini dkk., Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, (Gema Insani: Jakarta, 2013), hlm. xvii
59 ImÄm Muhammad ibn Muhammad al-ShawkÄni, IrshÄd al-FuhÅ«l ila al-TahqÄ«q al-Ḥaqq min ‘Ilmi l-UshÅ«l, (Beirut: DÄr al-KutÅ«b al-IslÄmiyyah, 1994), hlm. 71,2. Dikutip dalam Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, hlm. 207-208
60 Adi Setia “Epistemologi Islam Menurut al-Attas Satu Uraian Singkat†dalam ISLAMIA: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, Tahun II (Nomor.6, Juli-September 2005), hlm. 54
61 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme…., hlm. 207
62 Ibid, hlm. 210
63 Lebih jelasnya silahkan baca, Jalaluddin as Suyuti, al Itqan fi ‘Ulum-l Qur’an, (al Maktabah al ‘Ashri, 2003)
64 M. Mustafa al-A’Zami, Sejarah Teks Al-Qur’an dari Wahyu Hingga Kompilasi: Kajian Perbandingan dengan Perjanjian lama dan Perjanjian Baru…., hlm. 43-128. Untuk lebih jelasnya baca, al-Sayyid Ahmad bin Abd Rahman, AsÄnid Al-QurrÄ’ al-Asharah al-BarÄrah wa RuwwÄtihim al-BarÄrah, (Kairo: DÄr al-á¹¢ahÄbah, 1424)
65 Lihat hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah RA. Fatimah berkata, "Nabi Muhammad memberitahukan kepadaku secara rahasia, Malaikat Jibril hadir dan membacakan al-Qur’an kepadaku dan aku membacakannya sekali dalam setahun. Hanya tahun ini ia membacakan seluruh isi kandungan al-Qur’an selama dua kali. Aku tidak berfikir lain kecuali, rasanya, masa kematian semakin dekat." Lihat Shahih Bukhari, Faá¸a’il al-Qur’Än, 7
66 Konsep-konsep dalam al-Qur’an yang begitu banyak dan kaya kemudian dipahami dan ditafsirkan oleh para sahabat, tabi’in, tabi’i tabi’in hingga para ulama saat ini. Konsep-konsep ini berakumulasi pada pemahaman wahyu yang masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan, lalu membentuk sebuah sebuah peradaban yang kokoh. Dengan kata lain, wahyu dalam tradisi Islam melahirkan sebuah budaya Ilmu atau tradisi intelektual yang bermuara pada terciptanya sebuah peradaban. Selain itu, dari wahyu ini pula Islam memiliki sebuah medium transformasi dalam bentuk sebuah institusi pendidikan yang disebut al-Suffah. Lihat, Alparslan Acikgenc, Islamic Science: Toward a Definition, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), hlm. 82-83. Juga, Hamid Fahmy Zarkasyi, “Ikhtiar Membangun Kembali Peradaban Islam yang Bermartabat†dalam On Islamic Civilization (ed) Laode Kamaluddin, (Unissula Press: Semarang, 2010), hlm. 25-26 dan Hamid Fahmy Zarkasyi, Peradaban Islam: Makna dan Strategi Pembangunannya, (Ponorogo: CIOS-ISID, 2010), hlm. 17
67 M. Mustafa al-A’Zami, Sejarah Teks Al-Qur’an dari Wahyu Hingga Kompilasi: Kajian Perbandingan dengan Perjanjian lama dan Perjanjian Baru…., hlm.46-66
68 Para sahabat kuttab ini di antaranya AbbÄn bin Sa’īd, Abu ‘UmÄma, Abu AyyÅ«b al-Aná¹£ari, Abu Bakr al-á¹¢iddÄ«q, Abu Hudhaifa, Abu á¹¢ufyan, Abu SalÄma, Abu AbbÄs, Ubayy bin Ka’ab, al-Arqam, Usaid bin Sa’Äd, Suhaim, HatÄ«b, Hudhaifa, Husein, Hanzala, Huwaitib, Khalid bin sa’īd, Khalid bin WÄlid, Al-ZubaÄ«r bin AwwÄm, Zubair bin ArqÄm, dll. Untuk lebih lengkapnya, lihat al-A’ZÄmi, KuttÄb al- Nabiy, (t.p, RiyÄd, 1981)
69 Jalaluddin al-SuyÅ«ti, al-ItqÄn fÄ« ‘UlÅ«m-l Qur’Än, (al-Maktabah al ‘Aá¹£hri, 2003), hlm. 163-165
70 Ibn AbÄ« Daud, al-Maá¹£hÄhif, Cetakan ke-6, (Beirut: Maktabah al-IslÄmi, 2003), p.209
71 M. Mustafa al-A’Zami, Sejarah Teks Al-Qur’an dari Wahyu Hingga Kompilasi: Kajian Perbandingan dengan Perjanjian lama dan Perjanjian Baru…., hlm. 46-92
72 Muhammad Husein Haekal, Abu Bakr al-Shiddīq, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 335
73 Ibn AbÄ« Daud, al-MashÄhif, Cetakan ke 6, (Beirut: Maktabah al-Islami, 2003), hlm. 143
74 QS al Hijr: 9 yang artinya, “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.â€
75 M. Mustafa al-A’Zami, Studies in Hadith Methodology and Literature, revised edition, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), hlm. 9
76 Adapun mengenai jumlah perawinya, para ulama berbeda pendapat. Namun, al-SuyÅ«ti (911 H) memaparkan bahwa pendapat yang terpilih adalah sepuluh orang. Lihat, JalÄludin al-SuyÅ«ti, TadrÄ«b al-RÄwi fi Sharḥ TaqrÄ«b al-NawÄwi, (Cairo: DÄr al-KutÅ«b al-HadÄ«thah, 1966), hlm. 177.
77 M. Mustafa al-A’Zami, Sejarah Teks Al-Qur’an dari Wahyu Hingga Kompilasi: Kajian Perbandingan dengan Perjanjian lama dan Perjanjian Baru, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 190
78 Muhammad Abu Laits Khoiru Abadi, ‘UlÅ«mul HadÄ«th Äá¹£iluhÄ wa mu’Äá¹£iluhÄ,…., hlm. 135
79 MahmÅ«d TahhÄn, TaisÄ«ru Musá¹alah al-HadÄ«th, Cetakan ke-5 (t.p, Saudi Arabia, 2000), hlm. 19
80 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme…., hlm. 209
81 Muhammad Ibn HibbÄn, KitÄb al-MajrÅ«hÄ«n min al-MuhadithÄ«n wa al-DhuafÄ’ wa al-MatrÅ«kÄ«n, (Aleppo: DÄr al-Wa’y, 1396 H), hlm. 62-88
82 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Historical Fact and Fiction, (Kuala Lumpur: UTM Press, 2011), hlm. xi
83 Imam Muhammad ibn Muhammad al-ShawkÄni, IrshÄd al-FuhÅ«l ila al-TahqÄ«q al-ḤÄq min ‘Ilmi al-Uṣūl, (Beirut: DÄr al-KutÅ«b al-IslÄmiyyah, 1994), hlm. 78-85
84 Selain yang telah disebutkan, Ibnu HibbÄn menambahkan: orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan menyebutkan alasan sebagai amal ma’ruf nahi mungkar, orang yang secara terang-terangan berdusta karena ia menganggap bahwa hal tersebut adalah boleh, berdusta untuk kepentingan duniawi, orang yang telah lanjut usia, “al-MukhtalithÅ«nâ€, orang yang mengajar dari buku karangan tanpa pernah belajar langsung kepada pengarang tersebut, “yuhaddithu bi al-kutubÄ«n ‘an syukhÄ«n lam yarÄhumâ€, orang yang suka memutarbalikkan fakta serta menyamakan otoritas semua perawi, orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh gurunya, orang yang mengajarkan apa yang didapat hanya dari dalam buku saja, orang yang jujur namun sering keliru, orang yang sering dimanfaatkan, orang yang tidak tahu bahwa karya tulisnya telah dimanipulasi, orang yang pernah berbuat salah secara tidak sengaja lalu menyadari kesalahan tersebut akan tetapi membiarkannya, orang yang sering mengabaikan perintah agama secara terang-terangan (fasiq), orang yang tidak menyebutkan sumber asal karena tidak pernah menemuinya, orang yang menyebarkan ajaran sesat, dan orang yang berdusta untuk menarik perhatian orang banyak dengan ceramah serta nasehatnya. Lihat, Muhammad Ibn HibbÄn, KitÄb al-MajrÅ«hÄ«n mi al….., hlm. 62-88
85 Ibid, hlm. 80 lihat juga ‘Ali KhatÄ«b al-BaghdÄdi, al-KifÄyah fi ‘Ilmi al-RiwÄyah, (Jam’iyyah DÄ’irÄt al-Ma’Ärif al-‘UtsmÄniyyah, 1357 H), hlm. 115-134
86 Imam Muhammad ibn Muhammad al-ShawkÄni, IrsyÄd al-Fuḥūl ila…., hlm. 78-85
87 Ada pula yang membaginya menjadi 4, ditambah dengan ẓanni al-thubÅ«t wa qaá¹â€™i al dalÄlah) Contohnya, hadist Rasulullah yang berbunyi ÙÙŠ كل خمس من الإبل شاة. Hadist ini memiliki arti makna yang jelas, tidak mengundang banyak arti, namun kebenaran sumbernya masih belum mutawatir. Lihat, ‘Abdul Karim ibn ‘AliÄ« ibn Muhammad al-Namlah, al-Madzab fi Uá¹£hÅ«l al-Fiqh al-MuqÄrin, Cetakan 1, Jilid 5 (Riyadh: Maktabah al-RashÄ«d, 1999), hlm. 2320-2321
88 Muhammad ‘Abdul AdzÄ«m al-ZarqÄni, ManÄhil al-FurqÄn fi al-‘UlÅ«m a- Qur’Än, Cetakan ke 2, Juz 2 (Matba’ah ‘IsÄ al-BÄbhi al-Jali wa Shirkah, t.t), hlm. 247
89 Seperti ayat al-Qur’an surah al-Baqarah: 228 (والمطلقات يتربصن بأنÙسهن ثلاثة قروء). Kata qurū’ memiliki makna ganda, dapat diartikan sebagai “haid†tapi bisa juga diartikan sebagai “bersih/suciâ€. Lihat ‘Abdul Karim ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Namlah, al-Madzab fi Uṣūl al-Fiqh al-MuqÄrin…, hlm. 2320-2321
90 ‘Abd WahhÄb KhallÄf, ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh, (Kuwait: DÄr al-Kuwaitiyyah, 1968), hlm. 35
91 Seperti sebuah hadist yang berbunyi: لاصلاة لمن لم يقرأ بÙاثØØ© الكتاب yang periwatannya masih belum mutawatir. Selain itu, hadist ini juga mengandung maksud ganda. Pertama dalil tentang shalat yang benar dimulai dengan membaca surah al-Fatihah. Kedua, tidaklah lengkap shalat, tanpa membaca surat al-Fatihah. Lihat, ‘Abdul Karim ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Namlah, al-Madzhab fi Uṣūl al-Fiqh al-MuqÄrin…, hlm. 2320-2321
E. Penutup
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam, manusia mendapatkan ilmu yang meyakinkan melalui penyatuan sumber kebenaran—pancaindra, akal, intuisi, khabar á¹£Ädiq—dalam satu kesatuan yang utuh, tidak dikotomis, parsial dan terpisah-pisah. Artinya, cenderung kepada salah satu dan menolak yang lainnya, bukanlah ciri khas epistemologi Islam. Selain itu, kebenaran dalam al-Qur’an dan hadist bersifat absolut dan pasti, serta validitasnya tidak diragukan.erkat sistem periwayatan secara turun temurun melalui khabar á¹£Ädiq yang benar-benar terverifikasi secara ketat dan tidak sembarangan. Ini berarti, kabar yang diterima haruslah benar-benar melaui proses penyaringan yang begitu ketat baik isi maupun narasumber yang meriwayatkannya. Maka, hanya kabar yang benar sajalah yang dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam.
Dengan kata lain, khabar á¹£Ädiq sebagai sebuah metode transmisi ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dipertanggungjawabkan secara ontologis dan epistemologis. Ontologis, karena wujudnya riil, nyata, dan terekam dalam jejak sejarah yang dapat dibuktikan. Epistemologis sebab khabar á¹£Ädiq bekerja secara saintifik dengan melibatkan cara kerja yang canggih, rumit, logis, dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Lebih dari itu, tradisi ilmiah catatan kaki dalam tugas-tugas ilmiah, yang menunjukkan tingkat akademis yang tinggi, adalah gambaran sederhana dari tradisi periwayatan khabar yang sudah digunakan berabad-abad di dalam tradisi epistemologi Islam. Bahkan dalam praktik riilnya, tradisi khabar tampak lebih canggih. Maka, dugaan serta asumsi para orientalis terhadap al-Qur’an dan hadist adalah keliru, terkesan mengada-ada, serta tidak didasari oleh asumsi dan bukti yang kuat. Kalaupun diteliti lebih mendalam, tuduhan yang dilempar terkesan kental dengan unsur tendensi daripada sikap akademis yang menjunjung tinggi intelektualitas dan sikap jernih dalam melihat realitas. Wallahu a’lÄm.
Daftar Pustaka
‘Abdul HamÄ«d ‘Umar, AhmÄd Mukhtar. Mu’jamu al-LughÄh al-‘Arabiyah al-Mu’Äshirah, Jilid 1, cetakan pertama (‘Alim al-KitÄb, t.t)
Abd Rahman, al-SayyÄ«d Ahmad bin. AsÄnid Al-QurrÄ’ al-AshÄrah al-BarÄrah wa RuwwÄtihim al-BarÄrah, (Kairo: DÄr al-á¹¢ahÄbah, 1424)
AbÄ« Daud, Ibnu. al-Maá¹£Ähif, Cetakan ke-6, (Beirut: Maktabah al-IslamÄ«, 2003)
Acikgenc, Alparslan. Islamic Science: Toward a Definition, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996)
Adi Setia “Epistemologi Islam Menurut al-Attas Satu Uraian Singkat†dalam ISLAMIA: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, Tahun II (Nomor.6, Juli-September 2005)
Al-BaghdÄdi, ‘AlÄ« KhatÄ«b. al-KifÄyah fi ‘Ilmi ar-RiwÄyah, (Jam’iyyah DÄ’irÄt al-Ma’Ärif al ‘UtsmÄniyyah, 1357 H)
Al-Farabi, ArÄ’ al-MadÄ«nah al-Faá¸Ä«lah, TahqÄ«q: Albert Nashri Nadir, (Beirut: DÄr al-Mashriq, 1973).
_______________. Fuṣūṣ al-ḤikÄm, Tahqiq: Muhammad HasÄn ‘Ali YasÄ«n, (BaghdÄd: DÄr al-Ma’Ärif, 1976),
Al-GhazÄli, ImÄm. al-Munqidz min al-ḌalÄl, Tahqiq: JamÄ«l Shaliban, (Beirut: DÄr al-Andalus, 2003)
______________. IhyĒ Ulūm al Dīn, Juz 1, (Beirut: Dar Qolam, t.t)
______________. KimiyÄ’ Sa’Ädah in Majmū’ RasÄil Ghazali.
______________. MishkÄt al-AnwÄr, (Beirut: DÄr Qutaibah, 1990).
______________. Mi’yÄr al-‘ilm, tahqÄ«q; bi SulaymÄn Dunya, (Kairo: DÄr al-Ma’ÄrÄ«f, 1961).
______________. MizÄn al-‘Amal. Diedit oleh; SulaymÄn Slaim al-BawwÄb, (Damascus: DÄr al-Ḥikmah, 1986)
Al-KhalÄ«l Ibnu Ahmad, AbÅ« ‘AbdurrahmÄn. KitÄbu al-‘Aini, Jilid 8 (DÄr Maktabah al-Hilal, t.t)
Al-Khuli, ‘Alī Muhammad. a Dictonary of Islamic Terms, (tanpa tahun, pdf)
Al-TaftazÄni, Sa’Äd al-DÄ«n. A Commentary on the Creed of Islam: Najm al-DÄ«n al-Nasafi, translated and notes, Earl Edgar Elder, (New York: Columbia University, 1950)
Al-ZarqÄni, Muhammad ‘Abdul ‘Aẓim. ManÄhil al-FurqÄn fÄ« al-‘UlÅ«m al-Qur’Än, Cetakan ke 2, Juz 2 (Maá¹ba’ah ‘ĪsÄ al-BÄbhi al-JÄlÄ« wa Shirkah, t.t).
Al-A’Zami, M. Mustafa. Studies In Hadith Methodology and Literature, revised edition, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002).
______________. KuttÄb al-NabÄ«, (t.p, Riyad, 1981).
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Historical Fact and Fiction, (Kuala Lumpur: UTM Press, 2011)
________________. Islam and the Secularism, (Kuala Lumpur: IBFIM, 2014).
______________. Prolegomena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001).
_______________. Islam dan Filsafat Sains, terj: Saiful Muzani, (Bandung: Mizan, 1989).
Arif, Syamsuddin. Orientalis dan Diabolisme Pemikiran,( Jakarta: Gema Insani, 2008)
Armas, Adnin. Krisis Epistemologi dan Islamisasi Ilmu, (Ponorogo: CIOS-ISID, 2007)
Al-SuyÅ«ti, JalÄluddÄ«n. Al-ItqÄn fi ‘UlÅ«m-l Qur’Än, (al-Maktabah al-‘Aá¹£ri, 2003)
______________. TadrÄ«b al-RÄwi fi Sharh TaqrÄ«b al-NawÄwi, (Cairo: DÄr al-Kutub al-ḤadÄ«thah, 1966)
Al-ShawkÄni, ImÄm Muhammad ibn Muhammad. IrshÄd al-Fuḥūl ila al-TaḥqÄ«q al Ḥaqq min ‘Ilmi l-UshÅ«l, (Beirut: Dar al-KutÅ«b al Islamiyyah, 1994).
BaalbÄki, RohÄ«. Al-Mauriá¸, Edisi ke-7,( Beirut Lebanon: DÄr al-‘Ilm li al-MabayÄ«n, 1995).
Chittick, William C. Kosmologi Islam dan Dunia Modern: Relevansi Ilmu-Ilmu Intelektualisme Islam, terj Arif Mulyani, cetakan pertama, (Bandung: Mizan, 2007).
Daiber, Hans. “The Way from God’s Wisdom to Science in Islam: Modern Discussions and Historical Background,†dalam Islamic Science and the Contemporary World: Islamic Science in Contemporary Educations, (ed) Baharudin Ahmad, (Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, 2008).
Dewi Kania, Dinar. Epistemologi Syed Muhammad Naquib al-Attas, makalah.
Fajrie Alatas, Ismail. Sungai Tak Bermuara: Risalah Konsep Ilmu Dalam Islam Sebuah Tinjauan Insani, (Jakarta: Diwan, 2006).
Guillaume, Alfred. The Traditions of Islam: An Introduction to the Study of Hadith Literature, (Oxford: Clarendon Press, 1924).
Husaini, Adian. dkk., Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
Husein Haekal, Muhammad. Abū Bakr al-Shiddīq, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2010).
Ibn HibbÄn, Muhammad. KitÄb al-MajrÅ«hÄ«n min al-MuḥaddithÄ«n wa Ḍhu’afÄ’ wa al-MatrÅ«kÄ«n, (Aleppo: DÄr al-Wa’y, 1396 H)
Ibn Rusyd. Talḥis KitÄb al-Nafs, tahqiq: Ahmad Fuad AhwÄni, (Kairo: Maktabah al-Nahá¸ah al-Mishriyah, 1950)
Ibn Sina. AḥwÄl, al-Nafs: RisÄlah fi al-Nafs wa al-BaqÄ’ihÄ wa al- Ma’ÄdihÄ, tahqiq: Ahmad Fuad AhwÄni, (Paris: Dar Babylon, 2007).
Jeffery, Arthur. Materials for the History of the Text of the Qur’an: the Old Codices, (Leiden: E.J. Brill, 1937)
Kartanegara, Mulyadhi. Menyibak Tirani Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam, (Bandung: Mizan, 2005)
KhallÄf, Abd WahhÄb. ‘Ilmu UshÅ«l al-Fiqh, (DÄr al-Kuwaitiyyah: Kuwait, 1968)
Khairu abadi, Muhammad abÅ« Laits.‘UlÅ«mul Ḥadist ĀṣiluhÄ wa Mu’Äá¹£iluhÄ, (Malaysia: DÄrul ShÄkir, 2011)
MadkÅ«r, Ibrahim. Mu’jamu al-Falsafah, (Mesir: Hai’ah al-‘Ammah li al-Shu’ūn al-Maá¹ba’ al-AmÄ«rah, 1983).
Mohammad Iqbal, Allama. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, tanpa tahun dan penerbit, pdf
Muhammad al-Namlah, Abdul KarÄ«m ibn ‘AlÄ« ibn. Al-MadzhÄb fi UsÅ«l al-Fiqh al-MuqÄrin, Cetakan 1, Jilid 5 (Riyadh: Maktabah al-RashÄ«d, 1999)
Muir, William. The Life of Mahomet and the History of Islam to the Era of Hegira, Jilid 4 (t.p London, 1861)
Muslih, Mohammad. Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Belukar, 2008)
Muthahhari, Ayatullah Murtadha. Pengantar Epistemologi Islam, trj M. Jawad Bafaqih, (Jakarta: Shadra Press, 2010)
Nasr, Syeed Hossein. Encyclopedia of Islamic Philosophy, part I, (Lahore Pakistan: Suhail Academy, 2002)
Rescher, Nicholas. Epistemology: an Introduction to the Theory of Knowledge, (USA: State University of New York, 2003).
Schacht, Joseph. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, cetakan kedua, (Oxford: Clarendon Press, 1959)
Suharto, Ugi. “Epistemologi Islam†dalam buku On Islamic Civilization (Semarang: Unissula Press, 2010)
TahhÄn, MahmÅ«d. TaisÄ«ru Musá¹alaḥ al-ḤadÄ«th, Cetakan ke 5 (t.p, Saudi Arabia, 2000)
Taymiyyah, Ibnu. ‘Ilmu al-ḤadÄ«th, (Lebanon: DÄr al-KutÅ«b al-‘Ālamiyyah, 1985)
Titus, Harold H. Persoalan-Persoalan filsafat, Terj, H. M. Rosjidi, (Bulan Bintang: Jakarta, 1984)
Wan Daud, Wan Mohd Nor. “Beberapa Aspek Pandang Alam Orang Melayu dalam Manuskrip Melayu Tertua al-Aqa’id al-Nasafi†dalam Afkar: Journal of ‘Aqidah and Islamic Thought, Bil.6, (Kuala Lumpur: University of Malaya, Mei 2005).
______________. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas, (Bandung: Mizan, 1998)
Zarkasyi, Hamid Fahmy. “Ikhtiar Membangun Kembali Peradaban Islam yang Bermartabat†dalam On Islamic Civilization (ed) Laode Kamaluddin, (Semarang: Unissula Press, 2010)
______________. al-Ghazali’s Concept of Causality: With Reference to His Interpretations of Reality and Knowledge, (Kuala Lumpur: IIUM, 2010)
______________. Peradaban Islam: Makna dan Strategi Pembangunannya, (Ponorogo: CIOS-ISID, 2010)