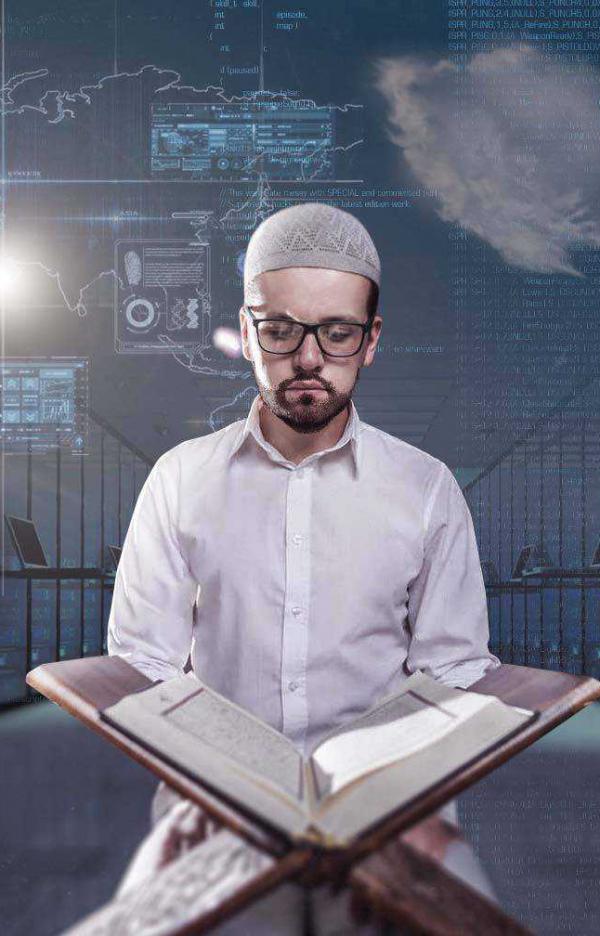Mohammad Natsir lahir di tengah gelombang besar pembaharuan Islam yang tengah melanda dunia Islam pada awal abad ke-20. Beliau berasal dari Sumatra Barat, tempat persemaian gerakan pembaharuan Islam dimulai, yakni sejak akhir abad ke-19. Gerakan pemurnian agama Islam dari bentuk-bentuk penyimpangan disertai pembaharuan pendidikan sedang berlangsung. Pergolakan sosial dan pertentangan kaum tua dan kaum muda menjadi sesuatu yang hal yang biasa ketika itu.
Para ulama muda yang baru pulang dari Timur Tengah mencoba membangkitkan kembali Islam. Sementara kaum yang sering dianggap mewakili kaum tua tetap berusaha mempertahankan yang telah menjadi kebiasaan di Minangkabau. DR. Haji Abdul Karim Amrullah (HAKA), DR. H. Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Djamil Djambek, Syekh Muhammad Thaib Umar, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dan Syekh Daud Rasyidi ialah ulama-ulama muda yang tengah menggencarkan pembaharuan di Sumatera Barat. Pergulatan antara kaum pembaharu dan adat Minangkabau itu terungkap dalam Islam dan Adat Minangkabau. [1]
Di tengah masyarakat yang sedang mengalami bermacam ketegangan sosial sedemikian, Mohammad Natsir lahir dan bertumbuh. Ia lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebagai anak Minang, ia tentu mengaji. Tetapi, selain mengaji di surau, Natsir kecil pun mengikuti pendidikan resmi. Ia tercatat sebagai murid Sekolah Rakyat Maninjau dan melanjutkan ke Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Adabiyah di Padang. Sempat pula pindah ke HIS Solok.
Perpaduan antara mengaji dan bersekolah telah menjadi sesuatu yang umum kala itu. Para pembaharu menekankan pentingnya umat Islam menguasai ilmu; bukan hanya ilmu-ilmu agama, melainkan juga ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah resmi. Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). [2]
Selepas lulus dari MULO, Natsir (pada usia 17 tahun) merantau ke Bandung untuk belajar di Algemeene Middelbare School (AMS) hingga tamat pada tahun 1930. Di sinilah Natsir mengasah aktivismenya dan bergabung dengan para pembaharu lainnya. Ahmad Hassan ialah salah satu tokoh penting dalam kehidupan Natsir remaja. Guru Persatuan Islam (Persis) itulah yang mengarahkan dan mengasah paham keagamaan Natsir. Kita mengenal A. Hassan sebagai seorang tokoh modernis yang gigih melakukan pemurnian ajaran Islam. Natsir, secara formal, menempuh pendidikan Belanda, namun ia juga mengaji pada tokoh pembaharu tersebut.
Selain bersama A. Hassan, Natsir pun terbiasa membahas beragam persoalan bersama seorang tokoh kharismatik dalam sejarah Indonesia, Haji Agus Salim. Perbincangan mengenai hubungan Islam dan negara telah banyak dibahas pada masa itu. Natsir tentu mewarisi pandangan-pandangan para modernis yang diperkenalkan oleh A. Hassan dan Haji Agus Salim.
Pengalaman Natsir semakin kaya setelah persentuhannya dengan Soekarno yang ketika itu sama-sama tinggal di Bandung. Natsir sempat berpolemik dengan Soekarno mengenai persoalan poligami. Persentuhan ini dapat dipandang sebagai awal perdebatan yang kelak menjadi lebih rumit antara kaum nasionalis dan kaum Islam. [3]
Pola pendidikan yang dilalui M. Natsir ialah pola yang menjadi umum di kalangan pembaharu Islam. Pada satu sisi, Natsir muda belajar di sekolah Belanda, tapi di saat yang bersamaan, ia pun mengaji kepada tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Ilmu dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari dua sisi.
Umat Islam dituntut untuk menguasai “ilmu-ilmu umumâ€. Sains dan humaniora yang berkembang dan dikembangkan oleh peradaban barat dipelajari melalui saluran sekolah-sekolah formal. Ilmu-ilmu ini, pada masa itu, dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai. Sementara itu, selain penguasaan “ilmu-ilmu umumâ€, umat Islam pun dituntut untuk menguasai “ilmu-ilmu agamaâ€.
Akan tetapi, “ilmu-ilmu agama†yang berkembang ketika itu dipahami sebagai ilmu-ilmu yang secara langsung berhubungan dengan al-Qur’an dan Sunnah beserta turunannya seperti fiqih dan akidah. Pandangan semacam ini pula yang kemudian dianut Mohammad Natsir ketika mengembangkan pendidikan partikelir di Bandung pada tahun 1930-an.
Selepas lulus AMS, putra Minang ini memang tak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan tak ada tawaran atau tak mampu, ia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan, berikhtiar mencerdaskan bangsanya. Visi perjuangan Natsir semakin terasah. Sampai pada akhirnya, ia berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan partikelir: Pendidikan Islam (Pendis).
Pendis ialah sebuah ikhtiar untuk menggabungkan penyelenggaraan pendidikan umum dan pendidikan agama dalam satu lembaga. Setiap peserta didik mendapat dua pendidikan itu dalam satu sekolah. Ini ialah semacam uji coba awal dalam pembangunan pendidikan Islam di Indonesia. [4]
Di Bandung itu, Natsir bersentuhan dengan beragam aktivitas pergerakan. Pada 1928 sampai 1932, ia menjadi ketua Jong Islamieten Bond (JIB) Bandung. Sejak 1938, lelaki Minang ini telah bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan menjadi Pimpinan Cabang Bandung untuk partai ini sejak 1940—1942. Pada masa pendudukan Jepang, Natsir bergabung dengan Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI), lembaga yang kelak berubah menjadi Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
Selepas kemerdekaan Pak Natsir banyak menduduki jabatan penting di negara yang baru bebas dari penjajahan. Di beberapa kabinet awal, ia menjabat sebagai Menteri Penerangan dan kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri pada kabinet yang ke-10. Tentu saja nama Mohammad Natsir tak dapat diabaikan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa kita.
Bersama tokoh-tokoh lain, Pak Natsir membangun sekaligus mempertahankan Indonesia Merdeka. Salah satu peran pentingnya ialah mengeluarkan Mosi Integral yang mengatarkan beliau memegang amanah sebagai Perdana Menteri. Mosi Integral yang menghindarkan bangsa kita dari perpecahan. Bentuk negara yang kita rasakan hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hadir tanpa jasa besar beliau.
Pada masa berikutnya, keadaan bangsa Indonesia yang berada di bawah Demokrasi Terpimpin ala Soekarno, membawa Pak Natsir pada rumah tahanan di Madiun. Oleh Soekarno, Pak Natsir diberi cap kontra revolusioner karena jalinannya dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan penolakannya terhadap gagasan dan propaganda Nasakom sebagai konsep bernegara.
PRRI sendiri sering disalahpahami sebagai pemberontakan terhadap pemerintah ketika itu. Padahal, pada dasarnya, PRRI adalah gerakan koreksi terhadap pemerintah pusat yang sentratralistis sekaligus strategi dalam menghadapi PKI yang memiliki kedudukan politik yang semakin kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. [5] Masyumi yang tidak pernah terlibat secara langsung dengan gerakan-gerakan tersebut pun akhirnya dipaksa membubarkan diri.
Ia bersama M. Roem, Yunan Nasution, Isa Anshari, Anak Agung Gde Agung, Prawoto Mangkusasmito, Mochtar Lubis, Sultan Hamid, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Ventje Sumual, Rudolf Runturambi, dan tokoh-tokoh lainnya diasingkan di rumah tahanan di Madiun selama kurang lebih empat tahun. Penangkapan dan pengasingan berlatar belakang politik ini dilakukan tanpa pengadilan.
Pada Juli 1966, Pak Natsir memperoleh kebebasan dari rumah tahanan di Madiun. Dan setelah setahun menjadi tahanan kota, baru pada 19 Mei 1967 seluruh tahanan politik rezim Orde Lama itu mendapat pembebasan penuh. Pada rezim baru yang dipimpin oleh Soeharto ini, Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito mulai merancang gagasan untuk berpartisipasi penuh mendukung pemerintahan Orde Baru. Pada mulanya, mereka mengharapkan pemerintah bersedia merehabilitasi Masyumi. Akan tetapi, permintaan ini tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.
Stabilitas yang dikehendaki oleh Orde Baru dianggap terlalu sulit terwujud apabila Masyumi kembali hadir dalam politik Indonesia. Meski demikian, para tokoh Masyumi itu tidak ngotot, tidak pula putus harapan. Karena tidak mungkin lagi terjun ke politik, Pak Natsir mengalihkan kegiatannya; berdakwah memperbaiki kehidupan masyarakat.
Pada Februari 1967, dalam musyawarah yang dihadiri berbagai elemen umat Islam Indonesia di Tanah Abang, didirikanlah Dewan Dakwah lslamiyah Indonesia. Salah satu pernyataan Pak Natsir kala itu berbunyi, “Dulu kita berdakwah melalui politik, sekarang kita berpolitik dengan berdakwahâ€.
Walaupun tidak lagi berperan secara formal dalam pemerintahan Indonesia, aktivitas Pak Natsir di bidang dakwah bertambah luas di dunia internasional. Pada tahun 1957, ia mendapat bintang kehormatan dari Republik Tunisia untuk perjuangannya membantu kemerdekaaan negara-negara Islam di Afrika Utara. Tahun 1967, dia mendapat gelar Doktor HC dari Universitas Islam Libanon dalam bidang politik Islam.
Kemudian Kerajaan Saudi Arabia menganugerahkan pula Faisal Award pada tahun 1980 untuk pengabdian Pak Natsir pada Islam. Sebelas tahun kemudian, ia memperoleh Doktor HC dari Universitas Sains dan Teknologi Malaysia dalam bidang pemikiran Islam. Pak Natsir menjalin hubungan baik dan bekerjasama dengan banyak negara, termasuk dalam hal gerakan-gerakan pembaruan Islam yang berbasis pada pan-Islamisme.
Keterlibatan Pak Natsir dalam Petisi 50 yang mengkritik Suharto pada rezim Orde Baru membuatnya dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Aktivitas dakwahnya pun dilakukan dari kantor Dewan Dakwah Islamiyah di daerah Salemba. Ia banyak menerima kunjungan tokoh-tokoh dari dalam dan luar negeri. Ia meninggal dunia di Jakarta, 6 Februari 1993 dan dimakamkan di TPU Karet, Tanah Abang.
Dari pemaparan singkat ini, kita dapat melihat Mohammad Natsir sebagai anak tulen modernisme Islam di Indonesia. Sosok Pak Natsir sebagai seorang modernis tentu terlihat dalam banyak peristiwa. Pandangan-pandangan beliau tentang ibadah dapat menunjukkan hal ini. Pandangannya tentang Islam sebagai sesuatu yang harus bersesuai dengan pola hidup modern; Islam dapat hadir dalam segala unsur kehidupan modern. [6]
Dalam bernegara, pendidikan, dan bahkan ekonomi yang tengah berlangsung ketika itu, Islam diupayakan untuk dapat hadir. Islam ditempatkan sebagai sesuatu yang tak ketinggalan zaman, memiliki peranan di setiap zaman. Dalam waktu bersamaan, beliau pun berusaha untuk menjadikan Islam sebagai pengobat segala penyakit yang ditimbulkan oleh modernitas, seperti keterasingan diri dan masalah-masalah moralitas. [7] Pak Natsir menempatkan Islam sebagai sesuatu yang dapat bersesuaian dengan modernisme dan sekaligus dapat menjadi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh modernisme itu sendiri.
Persoalan-persoalan di dalam Masyumi yang kemudian membuat NU keluar dan mendirikan partai politik sendiri, sedikit banyak terpengaruh pula oleh hal ini. Selain soal-soal politik, keretakan di dalam Masyumi terpengaruh perbedaan cara pandang terhadap banyak hal antara kaum modernis dan tradisionalis. [8] Banyak peristiwa yang membuat singgungan kedua pihak meruncing. Deliar Noer menangkap jelas gejala ini dan memaparkan beragam persoalan kultural dalam tubuh Masyumi:
... Dalam hubungan ini Natsir berbeda dengan Sukiman. Natsir telah mempelajari Islam dengan dalam; ia termasuk ulama juga. Ia bergabung dan menjadi eksponen Persatuan Islam di Bandung di masa mudanya, dan sering menjadi pejuang pahamnya pada berbagai kesempatan. Adakalanya pada waktu sebelum perang ia turut serta mewakili organisasinya berdebat dengan pihak NU yang antara lain diwakili oleh Kiyai Wahab, tokoh yang pada tahun 1952 menghendaki agar pos menteri agama diserahkan kepada NU. [9]
Pada tahap ini, sebenarnya kita telah dapat mendudukkan Mohammad Natsir secara saksama. Gagasan-gagasan Pak Natsir tentang banyak hal berpokok pada pandangan para modernist Islam. Gagasannya tentang negara, Islam, dan tentang hubungan di antara keduanya dapat pula dilihat dari sudut pandang ini.
_______________________________________________________________
[1] Lihat Hamka, Islam dan Adat Minangkabau (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984).
[2] Ajip Rosjidi, M. Natsir: Sebuah Biografi (Bandung, Girimukti Pasaka, 1990), hlm 51.
[3] Ibid, hlm. 15—38.
[4]Op.cit., hlm. 201—211.
[5] Gusti Adnan, PRRI: Pemberontakan atau Pergolakan Daerah, 100 Tahun M. Natsir Berdamai dengan Sejarah. (Jakarta: Republika, 2008), hlm 225—226.
[6] M. Natsir, Islam dan Akal Merdeka (Jakarta: Hudaya, 1970). Pada buku ini terlihat bagaimana Natsir membangun argumen bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal. Pengertian akal yang tertuang dalam buku ini lebih cenderung pada makna rasio seperti biasa kita temukan dalam tradisi falsafah barat. Gambaran akal sebagai intelek, atau sebagai jiwa yang biasa kita temukan dalam tradisi Islam (khususnya pandangan kaum sufi) kurang terlihat.
[7] M. Natsir, Pesan Islam kepada Manusia Modern [Cetakan ke-2] (Jakarta: Media Dakwah, 2008).
[8] Penggunaan istilah modernist dan tradisionalis sering dilihat sebagai sesuatu yang tak tepat. Penggunaan kedua kata tersebut dalam tulisan ini semata-mata ditujukan demi kepraktisan dalam memaparkan persoalan.
[9] Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional: 1945-1965 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 89.