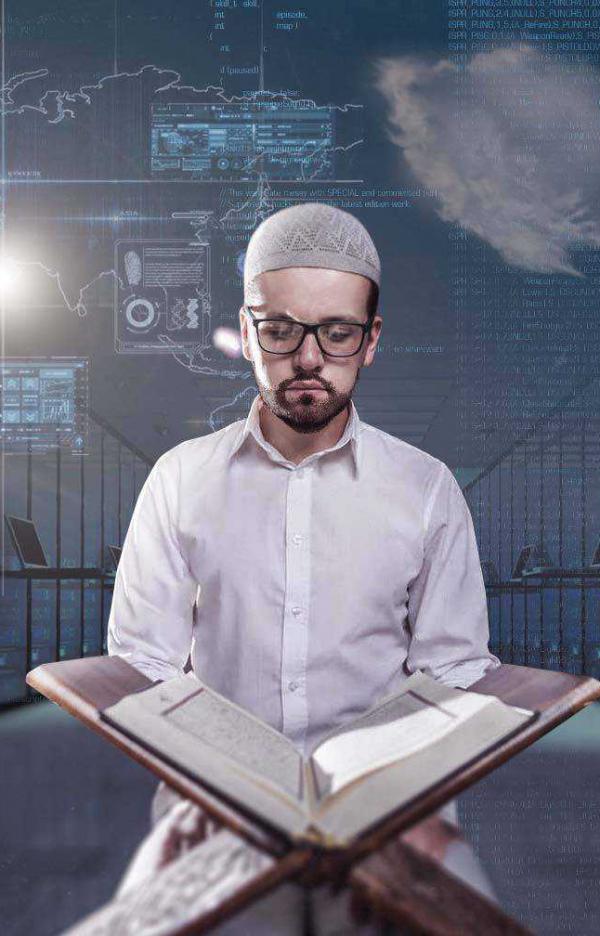Salah satu persoalan penting yang dihadapi kaum Muslim di awal abad ke-20 ialah pergaulannya yang panjang dengan Barat melalui penjajahan. Penjajahan yang dilakukan Eropa tidak hanya menyisakan sejarah kelam kemanusiaan tetapi juga menghadirkan sebuah tatanan pengetahuan yang telah tersekulerkan di hadapan umat Islam. Barat datang ke negara-negara Muslim dengan mengangkuti cara berpikirnya, cara pandangnya terhadap kenyataan dan wujud. Cara pandang yang sekuler, materialistis, dualistis, humanistis, rasional, dan tragis. Termasuk dalam persoalan ilmu. Barat “mengajarkanâ€, matematika, fisika, biologi, kimia, sosiologi, politik, bahasa, sastra, dan ilmu-ilmu lainnya sebagai sesuatu yang bebas nilai dan universal.
Pada sisi yang lain, umat Islam telah mengalami kemunduran dalam hal ilmu. Apa yang dipahami sebagai ilmu dalam Islam menyempit kepada Ilmu Al Qur’an (tafsir, qiraah, asbab al-nuzul), hadis, fikih, bahasa Arab, dan akidah. Ajaran tasawuf telah menyempit kepada sekadar akhlak, sementara ilmu-ilmu yang dipaparkan al-Khawarizmi, Ibn Haitham, Imam al-Ghazali, Fakhruddin al-Razi, dan lainnya terkubur di masa lalu. Muslim tak lagi mengenal bagaimana para ulama terdahulu membahas kimia, fisika, matematika, astronomi, dan lainnya.
Jika kita menelusuri tulisan-tulisan tokoh kita di awal hingga pertengahan abad ke-20 itu, kita dapat melihat hal itu secara jernih. Para tokoh kita masih memandang ilmu-ilmu yang dibawa oleh Barat itu sebagai sesuatu yang bebas nilai (netral/value free), bukan sesuatu yang penuh nilai (value laden). Sementara, pada ilmu-ilmu Islam, tokoh dan kaum Muslimin seperti mengalami keterpecahan, ketidakutuhan dalam menata ilmu-ilmu tersebut, khususnya dalam konsep metafisika.
Maka kita berhadapan dengan persoalan hadirnya “ilmu umum†(yaitu ilmu-ilmu yang dibawa Barat) dan “ilmu agama†(ilmu-ilmu Islam yang telah menyempit). Menghadapi persoalan tersebut, para pendahulu kita telah berikhtiar untuk menyandingkan “ilmu umum†dan “ilmu agamaâ€.
Uraian di bawah ini ialah salah satu yang menunjukkan hal tersebut. Bagaimana sebuah gagasan tentang negara diupayakan berkesesuaian dengan agama (Islam). Prawoto Mangkusasmito adalah tokoh penting umat Islam di Indonesia pada abad ke-20. Pak Prawoto adalah Ketua Umum Partai Masyumi ketika partai itu dipaksa membubarkan diri oleh Orde Lama. Uraiannya di bawah ini (termuat dalam tabloid Hikmah, 22 Syawal 1377, No. 13 Thn. XI-10 Mei 1958, hlm. 5—7) menunjukkan keterpengaruhan cara berpikir tokoh-tokoh Masyumi oleh gerakan modernis, termasuk Iqbal. Berikut ini ialah karangan Pak Prawoto tersebut.
Â
Misi Iqbal dan Cita-Cita Perjuangan Islam di Indonesia
Oleh: Prawoto Mangkusasmito
(Pidato pada Peringatan Hari Iqbal)[1]
Kami merasa mendapat kehormatan besar diminta turut serta oleh Kedutaan Besar Pakistan ikut menyambut Hari Iqbal ini. Walaupun kami khawatir kalau-kalau sambutan kami bukanlah seorang yang sudah menyelami ajaran-ajaran Iqbal, ibarat kata “sekadar sebagai musafir pernah sekilas pandang berpapasan di tengah jalanâ€, namun permintaan memberikan sambutan ini kami terima juga. Karena kami anggap peringatan Hari Iqbal ini tiap-tiap tahun adalah amat penting. Beberapa kelumit saja pengetahuan kami tentang pujangga Iqbal itu telah cukup memberikan keyakinan kepada kami tentang arti Iqbal. Yang jauh melebihi daripada semata-mata sebagai pujangga-nasional Pakistan saja.
Dengan peringatan semacam ini kita dapat mengenangkan kembali ajaran-ajaran dan cita-cita Iqbal sebagai ahli fikir dan pembangun bangsa Timur, terutama pula sebagai ahli pikir dan pembangun Muslim. Ajaran-ajaran Iqbal yang meliputi soal-soal dunia dan akhirat, soal-soal masyarakat dan metafisik, pantas dipelajari sebaik-baiknya dan kami percaya semua itu dapat mengilhami perihidup dan kehidupan kita.
Untuk kami sebagai seorang Muslim Indonesia, yang bercita-cita untuk menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan bernegara, maka misi Iqbal mempunyai arti yang khusus.
Apa sebab?
Mendasarkan kehidupan bernegara kepada ajaran agama, kepada Islam, berarti mengakui adanya pertanggung jawab terakhir yang terletak pada pertanggung jawab pribadi kepada Tuhan yang menjadikan kita sekalian. Pikiran-pikiran Iqbal mengenai soal pribadi ini yang sangat luas dan mendalam, rasa-rasanya penting sekali untuk dikenal dan dipelajari.
Pejuang Muslim manakah kiranya yang tidak akan tergetar hatinya oleh gema kata-katanya jika ia berseru dengan keberanian yang luar biasa: “Bangunlah pribadimu demikian hebat dan jayanya, sehingga sebelum Tuhan menentukan takdirnya bagimu, sudilah Dia bermusyawarat dengan kau dulu apakah kehendakmu sebenarnya.â€[2]
Di lain tempat ia mencanangkan kata-kata kepada umat Islam: “Kenapakah sungai hatimu tidak banjir melimpah. Dan kenapa khudimu tidak penjelmaan Muslim sejati. Apa gunanya berkeluh kesah tentang Takdir Yang Maha Kuasa. Jadilah sendiri hai umat, pencipta takdirmu!â€[3]
Mungkin kata-katanya ini adalah suatu konsepsi yang tidak lazim di sini. Kami sendiri tak ayal untuk menerimanya. Bukankah Tuhan sendiri telah berfirman di dalam Al Qur’an: “Innallaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim.â€
Kami kira mengandung kebenaran jika dikatakan bahwa struktur masyarakat yang ditimbulkan oleh kolonialisme di anak benua India/Pakistan semasa Iqbal banyak memperlihatkan kesamaan dengan apa yang kami jumpai di Indonesia ini.
Akibat dari masa yang silam itu hingga sekarang masih kami rasakan benar-benar adanya jurang yang memisahkan antara dua alam berpikir, dengan diikuti oleh norma-normanya masing-masing pula di segala macam segi kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini termasuk norma-norma seni dan susila.
Yang saya maksudkan ialah alam berpikir yang bersendikan pendidikan Barat, yang pada umumnya tak kenal nilai-nilai agama dan alam berpikir dari pesantren-pesantren yang pada umumnya jauh dari cabang-cabang pengetahuan yang bukan agama.
Adalah suatu keharusan untuk menutup jurang pemisah itu jika dikehendaki kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bulat, suatu condition sine qua non menurut hemat kami ke arah kemajuan dan kesempurnaan.
Perpaduan
Harus dicarikan bentuk perpaduan antara pandangan hidup yang bersendi kepada cara berpikir secara rasional-liberal dan dogmatis-formalistis. Jurang pemisah itu makin hari makin berkurang, dan adalah suatu kenyataan bahwa dalam usaha untuk mengecilkan akibat buruk daripada keadaan masyarakat yang belah (gespleten) ini, pelopor-pelopor dan pemimpin-pemimpin pergerakan Islam sejak setengah abad yang lalu itu dengan segala cara telah berusaha untuk memperkenalkan cita agama di kalangan masyarakat terpelajar Barat dan sebaliknya pergerakan-pergerakan Islam itu pula telah berusaha untuk memperkenalkan teori-teori pengetahuan Barat kepada masyarakat berpikir dari pesantren-pesantren.
Usaha daripada pergerakan-pergerakan Islam itu diakui belum sempurna, tetapi sebaliknya sewajarnyalah diakui pula bahwa usaha itu tidak kecil artinya bagi perkembangan alam pikiran Islam-modern di Indonesia ini.
Sekarang yang sangat diperlukan ialah memperdalam cara-cara untuk mendapatkan perpaduan berpikir yang berangsur menuju kesempurnaan. Kami kira untuk ini masyarakat terpelajar dan ahli pikir Muslim Indonesia, yang kini ikut bertanggung jawab dalam pendidikan dan pembinaan masyarakat Indonesia, tidak sedikit akan menemukan bahan bangunan (bouwstenen) di dalam karya pujangga Iqbal yang kita peringati sekarang ini.
Sinar wahyu Ilahi
Bukankah Iqbal telah sampai kepada ajaran-ajaran dan citanya sesudah menyelami dalam-dalam telaga ilmu, baik dari sumber para ahli pikir Timur seperti Djalaludin Rumi dan al-Ghazali, Ibn’l Farabi dan al Djili, maupun dari ahli pikir Barat seperti Kant dan Fitche, Nietche dan Bergson, ditambah dengan alam pikiran Yunani, ditempa dalam lembaga Qur’an dan hadis?
Bukankah dengan demikian kedalaman Iqbal dalam masalah-masalah agama dan keluasan Iqbal dalam alam pikiran Barat disinari dengan wahyu Ilahi menjadikan ia salah satu dari ahli pikir Muslim yang ideal untuk dapat menemukan harapan yang kami kemukakan di atas.
Iqbal memandang dunia Barat sebagai suatu dunia yang “materialistis†dan tak menghargai nilai-nilai agama dan itulah sebagai kesalahan yang pokok.
Ia memandang dunia Barat sebagai suatu kekuatan yang tak disertai cinta, dunia pengetahuan yang tak berjiwa. Sebaliknya, ia memandang dunia Timur, terutama dunia Islam pada masanya, sebagai dunia yang penuh cinta dan kerohanian tetapi tak ada pengetahuan dan kekuasaan dan tak ada usaha-usaha yang kreatif.
Timur harus mendapatkan pengetahuan dari Barat, tetapi Barat yang tak menghargai nilai-nilai agama harus kita jauhi benar-benar. Di dalam hubungan ini adalah tipis kata-katanya terhadap Kamalisme: “Musik Turki tak memainkan lagu baru. Barunya Turki adalah Eropa tua.â€[4]
Sebaliknya, dengarkanlah kritiknya terhadap orang Islam yang pasif: “Orang kafir di muka berhalanya dengan hati yang berjaga-jaga, adalah lebih baik daripada orang beragama yang tidur di mesjid.â€[5]
Harapan
Kalau peringatan-peringatan semacam sekarang ini dapat menimbulkan keinginan untuk mempelajari Iqbal lebih mendalam oleh generasi sekarang di Indonesia, maka itulah hasil yang sebesar-besarnya hasil yang dapat dicapai. Iqbal mempersoalkan persoalan-persoalan yang besar yang banyak menjadi persoalan kami pula. Apakah dengan demikian berlebih-lebihan jika Iqbal dikatakan pujangga kami pula? Kami rasa tidak. Oleh karena itu, pemikiran Iqbal mengenai persoalan-persoalan itu wajar rasanya untuk diketahui.
Semoga harapan kami ini menjadi kenyataan. Terima kasih.
[1] Hikmah, 22 Syawal 1377, No. 13 Thn. XI-10 Mei 1958, hlm. 5—7.
[2] Ashrar-I-Khudi (halaman 25)
[3] Idem (halaman 32)
(terjemahan Bahrum Rangkuti).
[4] “The Turk’s instrument plays no fresh tune. Its new is but the old of Europe†(Javid Namah p. 72).
[5] “An infidel before his idol with wakeful heart. Is better than the religious man asleep in the mosque.†(Javid Namah p. 40).